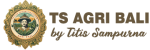Dewasa ini, salah satu tantangan yang dihadapi banyak negara agraria adalah ketiadaan standar yang jelas dalam mengatur kegiatan produksi di sektor pertanian dan perkebunan. Masing-masing negara tentu punya peraturan yang berbeda.
Namun, pada praktiknya, standar-standar ini tidak boleh lepas dari penerapan prinsip Good Agricultural Practice (GAP), alias praktik agrikultural yang baik. Nah, apa yang dimaksud dengan Good Agricultural Practice? Bagaimana petani serta pengelola kebun lokal bisa memanfaatkannya untuk hasil panen yang lebih berkualitas? Simak penjelasannya berikut ini.
Mengenal Good Agricultural Practice (GAP)
Menurut Food and Agriculture Organization of the United Nations, istilah Good Agricultural Practice mengacu pada serangkaian prinsip yang digunakan pada proses produksi dan pasca-produksi dalam industri pertanian dan perkebunan untuk menghasilkan produk pangan dan non-pangan yang sehat, aman, dan berkualitas.
Dalam praktiknya, prinsip ini juga tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, secara lokal, Good Agricultural Practice juga didefinisikan sebagai pedoman umum dalam melaksanakan budidaya pertanian dan perkebunan yang baik, untuk menjamin keamanan produk dan kesejahteraan petani serta ramah lingkungan.
Hal-hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP, antara lain adalah mengumpulkan, melakukan analisis, dan menyebarluaskan informasi praktik agrikultur yang baik dalam konteks geografis yang relevan. Tak hanya itu, petani, pihak pengemasan, hingga jasa pengiriman hasil tani juga didesak untuk lebih proaktif dalam meminimalisir bahaya keamanan pangan yang berpotensi buruk bagi produk pangan segar.
Semua pihak yang terlibat harus mengadopsi praktik yang menjamin kesehatan dan keamanan produk, termasuk petani, pemanen, distributor, eksportir, importir, perusahaan retail, hingga jasa pengemasan dan transportasi.
Jika sebuah bisnis pertanian atau perkebunan ingin menjajal pasar ekspor, maka sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan sertifikat GAP. Proses sertifikasi dilakukan oleh Kementerian Pertanian serta Lembaga Independen yang memiliki wewenang dalam melakukan penilaian serta penerbitan sertifikat GAP di bidang pertanian.
Penerapan Good Agricultural Practice di Indonesia
Sebagai salah satu sektor yang tetap tumbuh positif selama dan pasca pandemi, pertanian dan perkebunan di Indonesia terus digenjot untuk menjadi lebih baik. Penerapan GAP di negara kita sudah dimulai sejak tahun 2003, dengan komoditas sayuran sebagai target pertama.
Selanjutnya, Kementerian Pertanian secara berangsur mewajibkan semua produk hasil agrikultur yang diperdagangkan secara global untuk memiliki sertifikat Good Agricultural Practice. Produk-produk ini termasuk komoditas buah-buahan, kelapa sawit, rempah-rempah, kopi, teh, dan lain-lain.
Dalam praktiknya, GAP di wilayah ASEAN menekankan empat prinsip utama, yaitu :
- Keamanan konsumsi pangan;
- Jaminan kualitas produk dan penelusuran asal-usul produk jika diperlukan;
- Pengelolaan lingkungan yang benar; dan
- Jaminan keamanan, kesehatan, serta kesejahteraan pekerja lapangan.
Selain itu, terdapat pula beberapa komponen wajib yang harus dipenuhi produsen hasil tani dan kebun di Indonesia, agar bisa mendapatkan sertifikat GAP. Beberapa komponen wajib tadi antara lain adalah :
- Lahan yang dijadikan media tanam terbebas dari cemaran limbah beracun dan berbahaya
- Kemiringan lahan tidak lebih dari 30%
- Tindakan konservasi digunakan pada lahan yang miring
- Media tanam tidak mengandung cemaran dari bahan yang beracun atau berbahaya (B3)
- Pupuk yang digunakan harus disimpan dalam kamar atau gudang yang terpisah dari produk pertanian
- Kotoran manusia tidak boleh digunakan sebagai pupuk
- Pestisida yang digunakan harus dipastikan tidak kadaluarsa saat digunakan
- Pestisida disimpan dalam ruangan atau gudang terpisah dari produk pertanian
- Pelaku usaha dan petani mampu menunjukkan keterampilan dan pengetahuan dalam penggunaan produk pestisida
- Wadah untuk menampung hasil panen dalam keadaan baik, bersih, dan tidak terkontaminasi saat digunakan
- Air yang dipakai untuk mengairi irigasi tidak mengandung limbah dari bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)
- Hasil panen harus dicuci menggunakan air bersih
- Tempat atau area pengemasan hasil panen harus terpisah dari tempat penyimpanan pupuk dan pestisida
- Kemasan produk harus diberi label yang menjelaskan identitas dan asal-usul produk.
Keempat belas komponen di atas harus benar-benar diterapkan, mulai dari proses pembibitan, penyemaian, penanaman, panen, pengemasan, hingga pengiriman produk agrikultural, baik pangan maupun non-pangan.
Sumber : https://ukmindonesia.id/